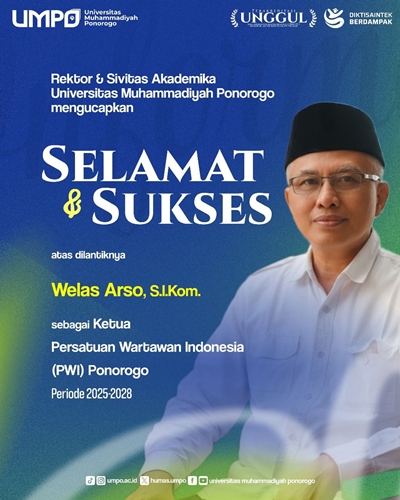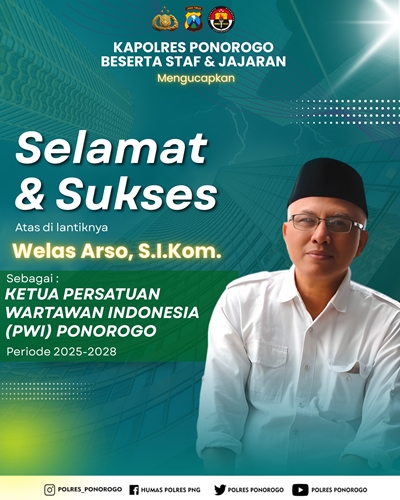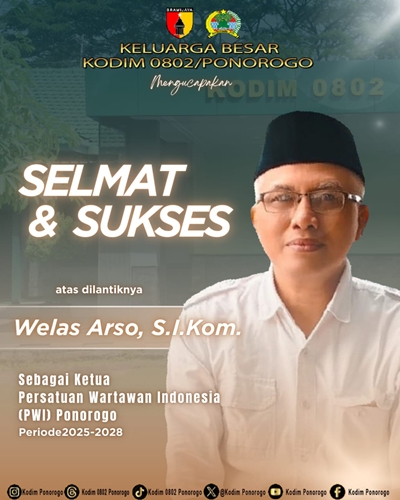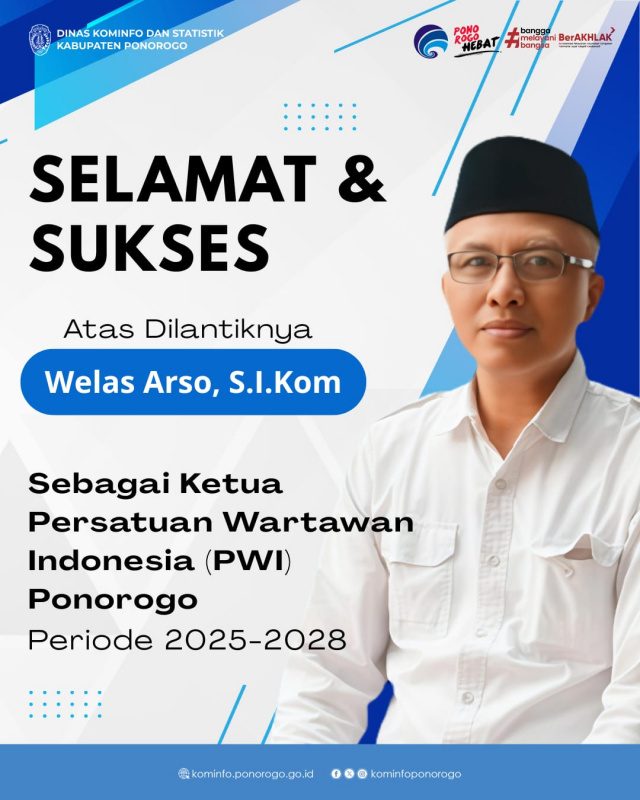Ahli: Percepatan PSN Buka Ruang Investasi Korbankan Hak Warga

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), pada Kamis (11/9/2025). Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 ini diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta 19 pemohon lainnya.
Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya. Dalam persidangan, para pemohon menghadirkan ahli hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial, Dianto Bachriadi Peneliti Senior Agrarian Resource Center (ARC), dan satu orang saksi.
Herlambang menilai, karakter hukum kebijakan dalam UU Cipta Kerja yang digunakan dibentuk dalam kerangka hukum neo-liberal. Prasyaratnya memang membutuhkan politik yang demokratis, terutama dibutuhkan untuk menunjang pembaruan hukum yang lebih bisa diterima pasar.
“Namun, prosesnya yang mendisiplinkan demokrasi diperlukan sebagai prasyarat untuk menginjeksikan program pembaruan hukum beserta kelembagaannya seraya tetap ramah pada liberalisasi pasar. Ini yang disebut sebagai ‘market friendly legal reform’ paradigm, atau paradigma pembaharuan hukum yang bersetia atau ramah pasar. Program pembaruan hukum dikemas dalam bingkai diskursus yang disahihkan melalui sirkuit kekuasaan dan legitimasi intelektual (kalangan proponen neo-liberal) dalam bentuk penarasian yang jamak digunakan, seperti human rights, good governance, access to justice, dan poverty reduction strategic programs,” ujarnya.
Menurut Herlambang, kebijakan ramah pasar tersebut, berada dalam posisi yang benar-benar meliberalkan pasar, tak terkecuali pasar tenaga kerja, peliberalan proses pengadaan tanah, serta kebijakan yang memungkinkan keuntungan sebesar-besarnya bagi investor atau pemilik modal. Tak mengherankan, gelombang pembaruan hukum dengan karakter hukum neo-liberal justru membuat buruh Indonesia yang kondisinya surplus menjadi rentan di-PHK.
“Proses peliberalan tersebut melahirkan tekanan atau pelanggaran bagi hak buruh, telah nyata bertentangan dengan hak-hak konstitusional, utamanya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2) dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2),” jelas Herlambang.
Ia juga menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam UU Cipta Kerja diposisikan sebagai komoditas dengan orientasi keuntungan bagi pemodal. Kebijakan yang mengedepankan “kemudahan dan percepatan” tersebut, menurutnya, memperlihatkan kecenderungan negara membuka ruang investasi dengan mengorbankan hak-hak warga, khususnya pekerja.
Herlambang menambahkan, jika pada era awal reformasi neoliberalisme lebih banyak dipengaruhi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, maka kini dorongan pembaruan hukum pro-investasi juga dipengaruhi oleh politik oligarki yang menguat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Selain Herlambang, para pemohon juga menghadirkan Dianto Bachriadi, Peneliti Senior Agrarian Resource Center (ARC). Dalam keterangannya, Dianto menegaskan cita-cita pembentukan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial, serta melindungi segenap bangsa. Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus merujuk pada norma dasar kehidupan bernegara yang termaktub dalam konstitusi.
“Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 cita-cita pembentukan negara ini dan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan negara ini bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial dan melindungi segenap bangsa. Segala sesuatu apa yang disebut pembangunan harus merujuk kepada norma dasar dalam kehidupan bernegara yang ada di konstitusi,” sebutnya.
Dianto menjelaskan, pengaturan kemudahan dan percepatan PSN dalam UU Cipta Kerja perlu ditinjau dari aspek konsistensi dengan konstitusi. Ia mengutip pemikiran filsuf hukum Gustav Radbruch untuk menilai apakah konsep hukum PSN sejalan dengan norma pokok kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen.
Lebih lanjut, Dianto memaparkan bahwa pada awalnya gagasan PSN hanya diatur melalui sejumlah Peraturan Presiden, mulai dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016 hingga Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Namun menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, konsep tersebut diangkat menjadi norma hukum setingkat undang-undang melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disusul Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.
Menurut Dianto, norma hukum terkait PSN dalam peraturan-peraturan tersebut lahir dari kewenangan Presiden dan penafsiran sepihak mengenai pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, lanjutnya, tidak ada penjelasan normatif maupun indikator terukur mengenai dua aspek tersebut. Ia juga menilai UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan percepatan PSN tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “nilai strategis nasional” yang mendasari kebijakan itu.
“Undang-undang ini hanya menyebutkan pengaturan terkait percepatan proyek strategis nasional sebagai bagian dari peningkatan investasi dan ekosistem usaha. Namun, norma yang lebih substantif tentang makna strategis nasional itu sendiri tidak ditemukan,” ujar Dianto.
PSN Rempang Eco City
Pada kesempatan yang sama, Pemohon juga menghadirkan seorang saksi yakni Sukri. Ia menyebut kehidupan sebelumnya sangat sejahtera dan berkecukupan, namun setelah adanya penetapan PSN Rempang Eco City, kualitas hidupnya menurun.
“Kami warga Rempang tersakiti ketika PSN ini masuk dimana ada intimidasi dari Pemerintah, aparat polisi,” ungkapnya.
Sukri menjelaskan penetapan PSN di Rempang sejak awal dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi warga Rempang sebagai pihak yang terdampak langsung. Pelaksanaan upaya pengadaan tanah untuk PSN Rempang Eco City telah terjadi penggusuran, konflik, serta tindakan kriminalisasi. Proses penggusuran tersebut melibatkan pengerahan aparat dalam jumlah besar, yakni lebih dari 1.000 personel dengan dukungan sedikitnya 60 kendaraan taktis untuk mengawal kegiatan pematokan lahan. Saat warga menolak, aparat menggunakan gas air mata yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Setidaknya 10 siswa dan satu guru SMP Negeri 22 Galang mengalami gangguan pernapasan, pusing, dan mual. Selain itu, seorang warga bernama Siti Hawa juga menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan karena menolak PSN Rempang Eco City.
Sebagai informasi, permohonan Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta 19 pemohon lainnya yang terdiri dari badan hukum privat dan perorangan warga. Materi yang diujikan dalam perkara ini ihwal pengaturan “kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)” dan/atau frasa “PSN” dalam Ketentuan Pasal 3 huruf d; Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2; Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4); Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1; Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3; Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15; serta Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).
Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), telah menggerus prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para Pemohon, berpendapat bahwa percepatan dan kemudahan PSN yang diatur dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja justru menimbulkan konflik sosial-ekonomi yang berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. Norma tersebut dianggap kabur (vague norm) karena memuat frasa seperti “penyesuaian berbagai peraturan” dan “kemudahan dan percepatan” yang tidak memiliki batasan operasional konkret. Hal ini dinilai membuka ruang bagi pembajakan kepentingan politik tertentu dan menutup ruang partisipasi publik yang bermakna.
Selain itu, sejumlah pasal lain dalam UU Cipta Kerja juga turut dipersoalkan, seperti Pasal 123 angka 2, Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 173 ayat (2) dan (4), serta Pasal 31 ayat (2). Ketentuan tersebut dianggap membajak konsep kepentingan umum dan hak menguasai negara yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945.
Dengan demikian, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka berharap, melalui permohonan ini, Mahkamah dapat memastikan akuntabilitas penyelenggara negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang kewajiban untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.