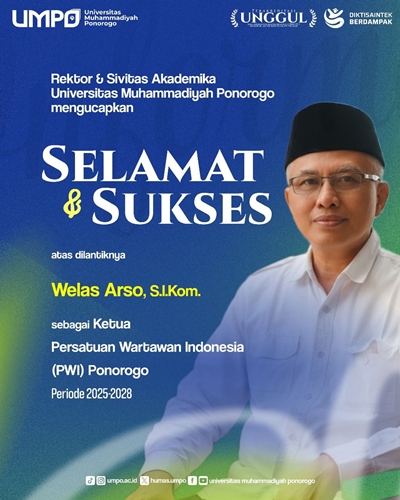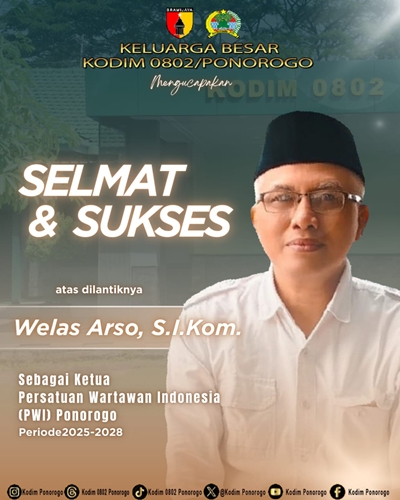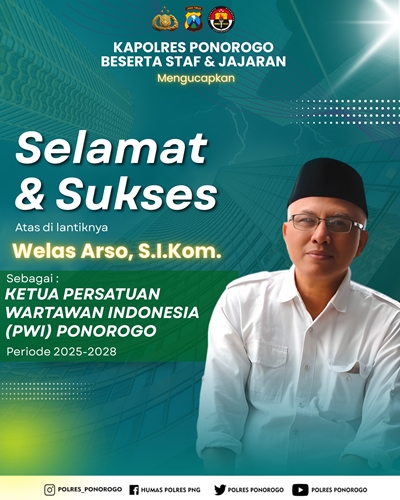Komnas HAM dan Komnas Perempuan Soroti Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan PSN

Ist
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM dan Komnas Perempuan hadir sebagai Pemberi Keterangan dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (7/10/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.
Anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian menilai pelaksanaan PSN berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak memenuhi prinsip hukum, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan serta kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan bukan sekedar alat meningkatkan angka statistik pertumbuhan ekonomi melainkan sarana memperluas kebebasan substantif warga negara. Akses terhadap ruang hidup yang layak, partisipasi bermakna dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan ini sejalan dengan deklarasi hak atas pembangunan yang ditetapkan PBB 1986 dan norma yang menempatkan manusia sebagai tujuan nasional.
Dalam konteks PSN, sambung Saurlin, pendekatan berbasis HAM mengharuskan norma dan praktik PSN memenuhi setidak-tidaknya syarat minimal kepastian hukum, partisipasi publik yang bermakna, perlindungan terhadap kelompok rentan beserta kelestarian lingkungan dan jika salah satu syarat tersebut gagal maka praktik PSN beresiko menimbulkan pelanggaran HAM. Kemudian, penyesuaian berbagai peraturan terhadap kemudahan dan percepatan PSN merupakan norma yang kabur karena tidak menjelaskan ruang lingkup kriteria objektif maupun mekanisme penetapan PSN.
“Ketidakjelasan ini membuka potensi multitafsir dan memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada Pemerintah maupun badan usaha sehingga hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) konstitusi berpotensi terlanggar. Norma ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum terabaikan secara prinsip Internasional mengenai rule of law yang diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat (1) ICCPR dan General Comment Nomor 16 Komite HAM PBB. Ketidakjelasan penetapan PSN dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja membatasi hak akses masyarakat terhadap informasi yang seharusnya terbuka. Hal ini menghambat partisipasi publik yang bermakna yang bertentangan dengan Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi,”ujarnya.
Selain aspek hukum, Komnas HAM juga menyoroti dampak lingkungan dari sejumlah proyek PSN yang menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air maupun udara. Beberapa kasus yang disoroti, antara lain Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Wadas, Makassar New Port, Kawasan Industri Hijau Indonesia, dan food estate Merauke.
“Pembangunan yang tidak berkelanjutan memperburuk krisis iklim dan mengancam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” kata Saurlin. Ia juga menyoroti penggunaan aparat keamanan dalam pengamanan proyek seperti di Rempang, Mandalika, dan Merauke yang dinilai menimbulkan kesan militerisasi pembangunan dan mengancam kebebasan berpendapat masyarakat.
Dalam keterangan tertulisnya, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi menegaskan setiap norma dalam UU Cipta Kerja harus tunduk pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. Norma yang kabur dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan diminta untuk dinyatakan inkonstitusional. MK juga diharapkan menafsirkan konstitusi secara progresif sebagai living constitution yang melindungi hak atas tanah, lingkungan, dan partisipasi publik.
Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah menyampaikan pandangan serupa dengan Komnas HAM terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai norma “kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)”. Maria mengungkapkan status PSN menghadirkan legitimasi hukum yang memberi percepatan izin, pembebasan lahan, dan pengerahan aparat negara, tetapi pada saat yang sama menegasikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang merupakan standar hak asasi manusia. Ia melanjutkan legitimasi inilah yang mengubah hukum menjadi instrumen kekerasan, sebab di balik wajah legalitasnya tersembunyi logika perampasan ruang hidup yang berdampak paling berat pada perempuan.
“Hilangnya sumber nafkah perempuan muncul dalam berbagai bentuk: laut yang tercemar reklamasi di Makassar, kebun yang dirampas untuk tambang batu andesit di Wadas, air bersih yang hilang akibat kerusakan Danau Poso, pangan hutan yang dirampas di Merauke, hingga usaha kecil yang hancur bersama penggusuran warung dan kios di Mandalika,” ungkap Maria.
Kemudian, Maria menjelaskan berdasarkan data pemantauan menunjukkan lebih dari seribu perempuan kehilangan sumber ekonomi langsung, sebuah angka yang menggambarkan pergeseran besar dari kemandirian ekonomi menuju ketergantungan yang dipaksakan.
Dalam keterangannya, Maria juga membeberkan sepanjang periode 2020–2024, Komnas Perempuan menerima 80 laporan pengaduan terkait konflik sumber daya alam, agraria, dan penggusuran. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi 11 (sebelas) laporan kasus yang secara langsung terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Pertama, Makassar New Port, 300 perempuan nelayan kehilangan nafkah, kemudian lonjakan KDRT. Kemudian yang kedua, Bendungan Bener, Wadas, Jateng. Ini juga 334 petani perempuan kehilangan tanah. Kemudian, Bendungan Mbay, Nagekeo, NTT. Intimidasi aparat, perempuan adat terluka, baik secara fisik maupun sosial. Kemudian yang keempat, PLTA Poso, Sulteng, 100 perempuan kehilangan akses air bersih. Kemudian yang kelima, PLTP Poco Leok, Manggarai, NTT. Ini juga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Kemudian yang keenam, PT Vale Indonesia, Sorowako, Sulsel. Ini juga puluhan perempuan kehilangan air bersih. Kemudian yang ketujuh, Merauke Food Estate, ini di Papua Selatan, ratusan perempuan adat kehilangan hutan, pangan, dan ruang hidup. Kemudian, UIII Depok, Jawa Barat, 17 perempuan kehilangan lahan usaha. Mandalika, NTB, 70 perempuan kehilangan usaha. Rempang Eco City di Batam, Kepri, perempuan luka fisik dan kehilangan lahan. Kemudian, di IKN Nusantara, perempuan adat alami pelecahan verbal dan kehilangan tanah,” urai Maria.
Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan terhadap 11 (sebelas) kasus PSN sepanjang 2020-2024, memperlihatkan pola konsisten bahwa status PSN bukan hanya percepatan pembangunan, melainkan juga instrumen legal yang menghasilkan bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender atau KBG. Ia menyebut KBG tersebut terbilang baru dan berlapis.
“Pertama, kekerasan fisik dan psikis. Dalam hampir semua kasus, aparat keamanan dikerahkan bukan untuk memberikan perlindungan kepada warga, melainkan untuk mengamankan proyek dan kepentingan investor. Dari berbagai perisiwa ini, sedikitnya 15 perempuan terdokumentasi mengalami luka fisik serius, terutama di Poco Leok, Rempang, dan Mbay yang menunjukkan pola kekerasan terukur dengan dampak langsung terhadap tubuh perempuan. Kekerasan fisik yang terjadi bukan sekadar tindakan represif sesaat, melainkan bagian dari reproduksi iklim teror yang berjangka panjang mengekang perilaku dan membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Maria.
Di akhir keterangannya, Maria juga menyebut pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengatur ‘kemudahan dan percepatan’ PSN bagi kepentingan para pengusaha merupakan tindakan diskriminatif karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menekankan kemudahan dan manfaat PSN seharusnya diprioritaskan kepada kepentingan masyarakat di lingkungan PSN dilaksanakan. Untuk itu, sambungnya, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon.
“Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadilan-adilnya (ex aequo et bono) untuk mendorong pada upaya-upaya penghormatan dan pemenuhan hak konstitusional warga, termasuk hak asasi perempuan,” tegasnya.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta 19 pemohon lainnya yang terdiri dari badan hukum privat dan perorangan warga ini menjadi Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), telah menggerus prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Para Pemohon berpendapat bahwa percepatan dan kemudahan PSN yang diatur dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja justru menimbulkan konflik sosial-ekonomi yang berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. Norma tersebut dianggap kabur (vague norm) karena memuat frasa seperti “penyesuaian berbagai peraturan” dan “kemudahan dan percepatan” yang tidak memiliki batasan operasional konkret. Hal ini dinilai membuka ruang bagi pembajakan kepentingan politik tertentu dan menutup ruang partisipasi publik yang bermakna.
Selain itu, sejumlah pasal lain dalam UU Cipta Kerja juga turut dipersoalkan, seperti Pasal 123 angka 2, Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 173 ayat (2) dan (4), serta Pasal 31 ayat (2). Ketentuan tersebut dianggap membajak konsep kepentingan umum dan hak menguasai negara yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945.
Dengan demikian, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka berharap, melalui permohonan ini, Mahkamah dapat memastikan akuntabilitas penyelenggara negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang kewajiban untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.(*)